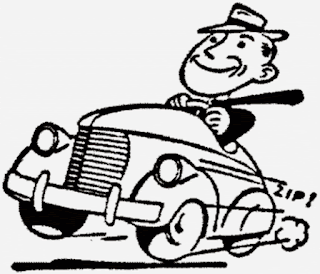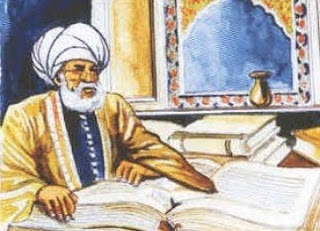Oleh T. Muntazar
Di pagi-pagi buta. Saat tetesan embun masih terasa. Cek Nurdin telah beranjak dari nyenyaknya tidur semalam. Nurdin sosok kepala keluarga yang bertanggungjawab terhadap anak dan istrinya. Pun bagi keluarganya yang sederhana itu, mereka menganggap Nurdin bagai seorang pekerja keras dan tak kenal lelah terhadap profesi yang sedang dijalaninya. Pagi-pagi sekali, Nurdin selalu bangun lebih cepat daripada anak-istri. Segera ia menuju beranda depan usai melaksanakan shalat Shubuh dan mulai membersihkan perkarangan rumahnya dari guguran daun jambu akibat angin semalam. Nurdin tak takut terhadap pagi yang basah, dan tak pernah lari dari cuacanya yang dingin, bahkan ia tak mengenal waktu untuk mengurungkan niatnya dalam berjualan sayur-sayur memasuki desa ke desa dan dusun ke dusun berikutnya.
“Sayur…sayur…yurrr…sayurrrrr”??? begitulah suara yang membahana tiap paginya saat ia mendagangkan sayuran dengan mendayung sepeda ontel tua peninggalan Almarhum Ayah. Diatur melingkar dan ditata rapi sayur-sayur segar itu pada keranjang yang terbuat dari rotan. Beragam jenis sayur-mayur yang ditawarkan Nurdin, diantaranya ada bayam, sawi, kangkung, daun singkong, daun melinjo dan beberapa jenis sayuran lainnya.
Anehnya, Nurdin cukup akrab dengan Ibu-ibu rumah tangga, para pembantu, dan gadis-gadis desa tempat ia menjajakan dagangannya. Pernah sesekali kaum ibu-ibu tak membayar langsung sayurnya pada Nurdin (berhutang) Namun hal demikian tak sedikit pun menjadi permasalahan baginya. Nurdin dikenal bagai pahlawan bagi ibu-ibu yang sedang kekurangan uang belanja.
Sangking fansnya para ibu-ibu terhadap budi dan kemurahan hati yang berselimut dalam jiwa Nurdin, mereka memberi sebuah julukan baru baginya, yaitu “Sayurudin”. Sungguh sepucuk nama yang sangat berarti bagi ibu-ibu yang merasa tertolong oleh jasa Nurdin, ia pun menerima pemberian gelar untuk dirinnya dengan lapang hati, tak menganggap sebagai pencemaran nama baiknya. Lagipula nama itu sudah terbentuk, dan tak mungkin diremove.
“Sayurudin”. Itu panggilan barunya sekarang. Sungguh nama yang diadopsi dari bidang pekerjaannya. Dan ia hanya tersenyum dan terus tersenyum mendengar panggilan itu. Kini, tak perlu heran dan ternganga atas sebuah nama atau gelar pemberian dari orang yang tak kita sadari mengagumi karakter kita. Memang begitu kekhasan yang terdapat dan telah membudaya pada masyarakat Aceh, seperti kata kleng yang melekat pada orang berwarna kulit hitam pekat, dan kata marra menempel pada orang berkebiasaan tingakah laku aneh. Mereka tak perlu banyak menimbang, memikirkan resiko untuk memberi segaris gelar baru terhadap orang-orang yang mereka anggap unik.
Monjen, 24 Juni 2012